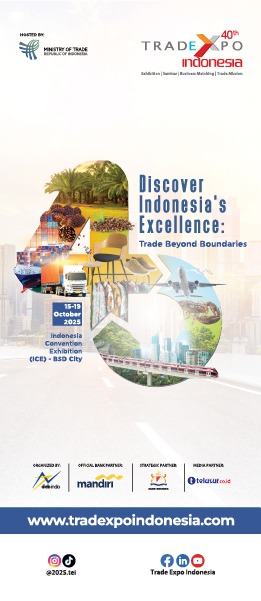Oleh: Suroto*
Pada waktu saya di Stockholm, Swedia, sekira tahun 2013, saya sempatkan berjalan-jalan melihat museum-museum kota ini yang jumlahnya sangat banyak sekali. Saya diantar seorang teman disana.
Pada satu perempatan, teman saya yang menyetir mengerem mobilnya di lampu merah perempatan agak mendadak. Lalu mobil kami tertabrak mobil lain dari belakang. Mobilnya peot keduanya. Lumayan parah kondisinya.
Pak Sopir dari dua mobil turun. Saya juga ikut turun memeriksa keadaan. Mereka sama-sama memeriksa keadaan dan sopir mobil yang menabrak kami langsung bertanya, "Apakah kamu baik baik saja?"
Teman saya jawab, "kami baik baik saja, bagaimana denganmu?"
Dia jawab, " Ya saya juga baik".
Kupikir mereka akan segera beradu argumen khas mencari pembenaran dan saling meninggikan intonansi suara. Seperti seringkali yang menimpa diriku ketika berserempet atau menabrak mobil lain di Jakarta.
Ternyata, kedua sopir itu buru-buru beradu cepat saling minta maaf. Teman saya langsung minta maaf pada pemilik mobil di belakangnya karena kesalahan dia yang mengerem secara mendadak.
Sopir mobil di belakangnya juga turun dan buru-buru meminta maaf karena merasa bahwa dia yang bersalah dan minta maaf karena sudah menabrak mobil kami. Dia bilang mustinya dia kendalikan diri dan jaga jarak.
Saya melihat orkestra yang indah sekali. Kedua orang itu pertama-tama pastikan bahwa keselamatan masing-masing orang yang lebih penting. Tidak membahas langsung kerusakan mobilnya seperti yang sering saya alami di Indonesia.
Kedua-duanya saling cepat meminta maaf dan mengoreksi kesalahan yang diperbuat. Mereka saling berebut menjadi pihak yang paling salah.
Tidak ada kata yang terdengar secuilpun sebagai tuduhan kepada salah satunya sebagai biang kesalahan. Lalu terakhir bukan perdebatan soal pembebanan pemberatan ganti rugi kepada salah satu pihak, tapi malahan saling menawarkan ganti rugi.
Debat cantik saling mengakui kesalahan, dan tawaran ganti rugi itu ditutup dengan masing-masing saling serahkan kartu nama untuk saling menghubungi apabila ada dana yang perlu diganti atau untuk perawatan kesehatan apabila mereka ada yang perlu berobat mungkin karena syok.
Saya cukup tertegun sejenak ketika melihat apa yang terjadi. Bagaimana bisa masalah itu berhasil ditangani dengan damai dan berakhir dengan indah.
Kuncinya adalah ternyata kata maaf, ya hanya kata maaf. Permintaan maaf yang tulus lalu tidak memdorong diri kita untuk menjadi pengeklaim posisi paling benar, tapi sama-sama melakukan koreksi ke dalam kesalahan yang dikontribusikan.
Saya membayangkan, kenapa tradisi masyarakat kota kita di Indonesia dan terutama di Jakarya ini tidak memperlihatkan hal ini? Kenapa orang orang kota ini kebanyakan menjadi begitu mudah untuk mengklaim diri paling benar terlebih dahulu dan lalu ingin segera menimpakan kerugian itu pada orang lain ketika hadapi masalah tabrakan yang sama?
Berulang kali saya terima kejadian yang mirip di Jakarta ini. Ketika saya berserempetan mobil bahkan saya terima makian dan kemarahan terlebih dahulu walaupun saya sudah awali dengan permintaan maaf. Saya sering juga katakan kalau tidak ada kesengajaan ataupun niat untuk mencelakakan orang lain.
Seringnya, semua kata-kata maaf saya tak digubris. Intinya saya selalu dalam posisi disalahkan dan harus ganti rugi. Ini saja yang saya selalu terima. Bahkan dua kali saya temui kejadian tragis yang menimpa saya ketika ditabrak, mereka langsung lari begitu saja.
Saya benar-benar selalu dihantui rasa takut ketika sewaktu-waktu menabrak atau ditabrak. Sebab saya hanya punya satu bayangan: salah!
Bahkan, sudah mengeras di otak saya dan selalu membuat panik ketika saya harus hadapi apapun masalah di jalanan.
Kenapa tradisi seperti ini terus dihidupi di negeri ini? Inikah konsekwensi modernitas yang banal? Manusia modern yang egosentris?[***]
*) Anggota Komunitas Penumpang Dan Pemberi Tumpangan Mobil (KPPTM)