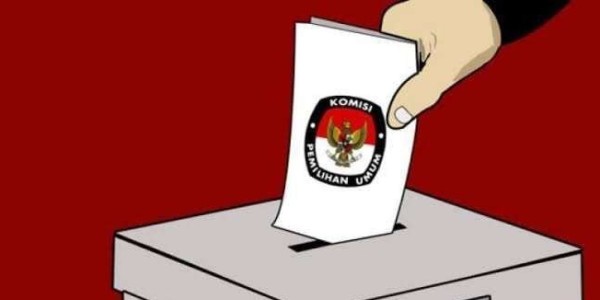Telusur.co.id - Oleh: Dr. Margarito Kamis, SH. M.um
Apa kerugian konstitusional anda, begitu sebuah pertanyaan terlontar lembut dari salah satu hakim MK kepada Pak Jendral (purn) Gatot Nurmantio dalam pemeriksaan pertama permohonan pengujian constitutionalitas presidential threshold di MK. Tidak itu saja, sang hakim juga menanyakan kepada Pak Jendral Gatot apakah dirinya pernah dicalonkan jadi presiden?
Menarik, pertanyaan pembuka tersebut diikuti dengan penegasan dari hakim lain dalam sidang itu. Dalam esensinya, penegasan sang hakim lain itu, kalau tidak salah professor Aswanto, bernada godaan pada pemohon mendemonstrasikan kekuatan argumentasinya. Katanya, kalau saja ada argumentasi baru, tentu meyakinkan, kami memiliki kemungkinan mengubah pertimbangan putusan yang sudah-sudah.
Sang hakim, dengan penegasannya itu, yang terlihat cukup meyakinkan. Ia menyediakan kemungkinan terjadi perubahan pertimbangannya, tentu dengan pijakan tak tergoyahkan dari argumentasi pemohon. Oke, logis sejauh itu. Sebab, dalam ilmu hukum level justifikasi putusan hakim terletak pada rationya. Ratio adalah jiwa, sumber dan kekuataan putusan.
Sidang ini, menariknya, menyajikan satu fakta, dapat disebut ultimate fact, MK telah memeriksa, mengadili dan memutus 15 (lima belas) perkara (permohonan) yang sama dalam semua aspeknya, dengan permohonan yang diperiksa saat ini. Pada titik itu, terasa logis menempatkan persoalan legal standing pemohon pada sumbu sorot.
Siapa di antara pemohon-pemohon yang sudah-sudah yang pernah dicalonkan jadi calon presiden? Profesor Yusril Ihza Mahendra misalnya, yang Partai Blan Bintang (PBB), partai yang menaungi Pak Profesor, yang pada tahun 2008 menjadi pemohon penghapusan presidential threshold, adalah salah satu yang nyata. Tetapi permohonan PBB tahun 2008, sama dengan sejumlah partai lain, di antaranya Hanura, semuanya ditolak.
Partai tak memiliki legal standing, dan perorangan juga tak memiliki legal standing, begitu esensi dari sebagian putusan-putusan sebelumnya dalam urusan JR presidential threshold. Legal standing juga yang menjadi sebab permohonan Bang Rizal Ramli, RR, kandas, tak diterima.
Tetapi sebelum lebih jauh berbicara sejumlah aspek teknis dalam urusan ini, marilah menganalisis lebih jauh konsep legal standing itu. Apa sebenarnya legal standing, tentu dalam perspektif ilmu hukum? Apakah legal standing memiliki sifat sebagai prinsip atau aturan, rules? Soal ini harus dibuat jelas, karena ilmu hukum, pada tingkat tertentu, membedakan prinsip dan aturan.
Legal standing, sejauh ini telah diberi kapasitas hukum sebagai hak berperkara, lebih tepat disebut hak mengajukan permohonan JR atas pasal, ayat atau huruf dalam UU, yang dinilai bertentangan dengan konstitusi di MK.
Soalnya adalah bagaimana hak itu timbul, dan dimiliki oleh pemohon?
Pada titik inilah muncul kerumitan konstruksi atas hak mengajukan permohonan JR. Soal itu harus dipecahkan. Bagaimana penalarannya? Dalam kerangka itu, maka sekali lagi, bagaimana seseorang menganggap memiliki hak, dari mana dan dengan cara apa hak itu muncul dan dimiliki pemohon, harus dijadikan prioritas identifikasi dan kategorisai masalah.
Apakah status kewarganegaraan pemohon logis dijadikan pijakan konstruksi i lahirnya hak pada pemohon, sehinga pemohon dengan sendirinya memiliki hak itu? Bila itu dasarnya, maka soalnya adalah bagaimana menginferensi restriksi-restriksi dalam pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Pasal ini mengatur syarat, kualifikasi personal, yang dilihat dari sudut ilmu hukum harus dipenuhi untuk menjadi presiden.
Dalam ilmu hukum konsep syarat, beresensi sebagai hal hukum atau keadaan hukum yang padanya bergantung keabsahan atau sebaliknya ketidakabsahan keadaan obyek hukum lain. Syarat, dengan demikian, mengandung unsur imperatif adanya satu atau serangkaian obyek atau keadaan hukum baru yang sah. Keadaan hukum inilah yang melahirkan adanya sifat sah, misalnya hak, yang semula tidak ada menjadi ada dan sah.
Sebaliknya, syarat juga, dapat, sesuai sifatnya meniadakan atau menangguhkan atau menghapuskan keabsahan keadaan hukum yang eksis, yang melekat pada satu obyek.
Konsekuensinya, dalam kasus pengujian presidensial threshold, hak mengajukan permohonan, dalam sifat esensisnya, tidak demi hukum telah ada, melekat dan dimiliki oleh pemohon.
Bagaimana membuat hak itu dianggap secara hukum telah ada dan dimiliki oleh pemohon? Pada titik ini diperlukan kecermatan inferensi terhadap dua hal. Kedua hal itu adalah “prinsip” dan “aturan, rules” sehingga tidak menimbulkan indeterminacy. Ilmu hukum memandu dunia hukum dengan prinsip atau asas “kerugian dianggap ada bila dan hanya itu, dipertalikan dengan hak. Tidak lebih.
Seseorang, siapapun dia, tidak dapat dinilai menderita kerugian, materil maupun moril, bila tidak ada hak yang dimiliki. Tanpa hak, tidak seseorang pun bisa bicara mengenai kerugian. Tanpa kerugian, tidak logis menemukan alasan untuk mengajukan permohonan menuntut ganti rugi, atau dalam kasus ini, memohon pembatalan pasal 222 UU Nomor 7 ahun 2017 Tentang Pemlihan Presiden.
Kerugian, baru logis dinyatakan ada bila pada orang tersebut melekat hak atau memiliki hak. Tanpa adanya hak, tidak akan ada kerugian. Hak menjadi sebab adanya kerugian. Kerugian menjadi sebab diajukan permohonan pembalan pasal yang merugikan itu.
UUD, harus diakui, memberi jaminan hak yang bersifat asasi, kepada setiap warga negara. Hak itu, salah satunya, kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi UUD juga tegas menyatakan pelaksanaan atau pemenuhan hak itu diatur oleh UU. Itu soal terbesar dalam kasus ini.
Apakah kesempatan yang sama menjadi prima causa lahirnya hak dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi presiden? Ini soal rumit. Dilihat dari sudut ilmu interpretasi, maka soal yang harus dipecahkan adalah apakah hak dicalonkan dan atau mencalonkan bersifat negatif atau positif?
Kalau hak dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi presiden ini bersifat negative, maka soalnya apa hukumnya pasal 6 ayat (2) UUD 1945? Pasal ini, sekali lagi, mengatur syarat menjadi presiden. Syarat selalu memiliki sifat membatasi. Hak yang bersifat negatif, tidak mungkin, dalam penalaran ilmu hukum konstitusi, dibatasi.
Menariknya, pasal 6 ayat (2) UUD 1945, berifat membatasi. Apakah kenyataan ini menandai UUD 1945 menganut prinsip hak asasi yang bersifat negatif dapat dibatasi? Terlihat tidak. UUD 1945, tegas menganut prinsip hak yang dapat dibatasi adalah yang bersifat positif, yang diberikan, disifatkan dan diciptakan oleh hukum, bukan hak yang bersifat alamiah.
Menariknya, tidak ditemukan satupun ketentuan hukum positif, baik samar-samar maupun eksplisit memberikan hak kepada setiap warga negara dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi calon presiden dan menjadi presiden. Praktis, hukum positif membatasi hak dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi calon presiden.
Kerugian konstitusional, untuk alasan apapun tak bakal memiliki justifikasi konseptual untuk dikonsepkan sebagai kerugian perdata. Presiden dan calon presiden, tak mungkin dalam perspektif ilmu hukum umum dan konstitusi, dikonsepkan sebagai benda, apalagi benda dengan sifat hukum perdata.
Norma-norma hukum, dalam semua unsurnya, tidak memiliki kualitas hokum perdata. Sama sekali tidak. Norma hukum, tidak pernah tidak merupakan konsep yang terangkai secara integrated menjadi hukum, dengan semua atribut khasnya. Itu sebabnya, pencarian hak dan kerugian konstitusional terasa logis menembus batas-batas praktis.
Pencarian yang beranjak dari sumbu epistemologis dan ontologis, terasa harus dilalui. Mengapa menciptakan republik, dan bagaimana eksistensi setiap orang, dalam sifatnya sebagai citizen, dan seperti kata-kata Madison dalam Federalis Paper No.51, “justice is the of government. Is the end of civil society” masuk akal digali. Pijakan kualifikasi ada atau tidak, pantas atau tidak legal standing melekat pada setiap warga negara, pasti membuat indah mozaik republik.
Inferensi sidang hanya dengan meminta pemohon, yang dalam esensinya, menyajikan fakta pernah atau tidak dicalonkan menjadi calon presiden, terasa memukul akal sehat. Tak cukup indah, karena tidak terlihat mozaik metodologis dan inferensi filosofis, sesuatu yang terasa perlu pada kasus sebesar ini.
Kelangkaan energi pencarian keindahan perspektif prinsipil republik, terasa pantas disudahi. Republik, yang dari lahirnya menuntun rindunya yang bersifat aksiomatik bahwa pengisian jabatan umum, harus melalui pemilu, mungkin pantas ditapaki.
Sungguh manis, rakyat, warga negara, disambut dan diperlakukan republik, dalam kata-kata James Madison pada Federalis Paper No.49 only legitimate fountain of power.” Pada Federalis paper No. 51, Madsion kembali menegaskan pendiriannya tentang prinsip dasar republik dalam pengisian jabatan supreme executive, legislative and judiciary. Dalam kata-katanya, Madison menegaskan “should be drawn from the same fountain of authority, the people.” Top, berkelas. ***