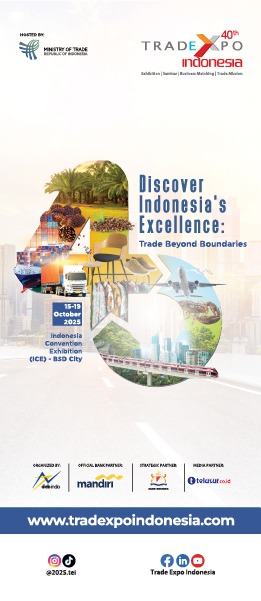Telusur.co.id - Oleh: Dr. H. Joni,SH.MH***
SEKURANGNYA ada 79 item perubahan mendasar pada level Undang Undang, termasuk dalam kaitannya dengan pengelolaan Suber Daya Alam (SDA) yang diadakan perubahan oleh UU Ciptaker. Satu diantaranya adalah pengelolaan Sumber Daya Perikanan. Analisis berikut mencatat bagaimana pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang menurut UU yang lama sebenarnya masih belum selesai, tetapi tenyata “ikut” diadakan perubahan oleh UU Ciptaker.
Pertumbuhan PDB Perikanan
CATATAN berikut adalah tahun 2015- 2019, yang mengalami kontraksi dari 7,89% pada tahun 2015, kemudian secara fluktuatif turun menjadi 5,19; 5,70%; dan 5,19% pada 2016, 2017, dan 2018, kemudian menjadi 5,81% pada 2019 (DJPB 2019. Namun, secara kinerja PDB sub-sektor perikanan budidaya menunjukkan tren meningkat, dari Rp. 102.422 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp. 144.795 miliar pada tahun 2019. Artinya, terjadi peningkatan share PDB perikanan budidaya terhadap PDB perikanan dari 50% pada tahun 2015 menjadi 57,9% pada tahun 2019 (BPS 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi perikanan budidaya yang positif dari tahun 2015-2019, mampu berperan dalam peningkatan kinerja ekonomi perikanan nasional.
Untuk nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) mengalami kenaikan rata-rata 0,6% per tahun pada periode tahun 2015-2019, yaitu dari 99,66 pada 2015 menjadi 102,09 pada 2019 (BPS 2019). Rata-rata NTPi tahun 2018-2019 telah dapat mencapai angka lebih besar dari 100, dimana pada 2015-2017 angka rata-rata NTPi selalu dibawah 100. Hal ini menunjukkan sejak 2018 terjadi perbaikan struktur ekonomi pembudidaya ikan yang diakibatkan oleh meningkatnya pendapatan pembudidaya.
Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan pada tahun 2015-2019 mengalami peningkatan 4,94% pertahun, dari Rp. 2,99 juta/bulan di tahun 2015 menjadi Rp. 3,62 juta/bulan di tahun 2019 (BPS 2019). Angka pendapatan tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata nilai Upah Minimum Regional (UMR) nasional, yaitu Rp. 1,69 juta/bulan di tahun 2015 menjadi Rp. 2,45 juta/bulan di tahun 2019. Peningkatan pendapatan pembudidaya ikan disebabkan oleh: (i) meningkatnya permintaan pasar terhadap komoditas perikanan budidaya; (ii) peningkatan produktivitas pembudidayaan ikan sebagai hasil penerapan teknologi anjuran; (iii) keberhasilan pelaksanaan program pembangunan perikanan budidaya.
Potensi Sangat Besar
Indonesia memiliki potensi perikanan budidaya yang besar dan perlu terus dimanfaatkan secara optimal, antara lain:
Pertama, Indonesia memiliki sumber daya / keanekaragaman hayati ikan yang melimpah. Beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti tuna, udang, lobster, sidat, kepiting, kakap, bawal, cobia, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan dan rumput laut. Demikian pula di perairan umum daratan seperti arawana, gabus, papuyu. Dengan melihat besarnya potensi dan manfaat perairan Indonesia, sudah seharusnya kelautan dan perikanan Indonesia menjadi penggerak baru ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. untuk ikan air tawar, Indonesia mempunyai keragaman hayati ikan yang tinggi, mulai dari ikan budidaya di kolam, seperti nila, lele, mas, gurame, patin, hingga ikan endemik.
Kedua, Luas lahan perikanan budidaya sangat besar dan dan dapat digunakan untuk berproduksi sepanjang tahun. Total potensi luas lahan perikanan budidaya sebesar 17,91 juta hektar, terdiri dari budidaya laut sebesar 12,12 juta hektar, budidaya air payau sebesar 2,96 juta hektar, dan budidaya air tawar sebesar 2,83 juta hektar (KKP 2019). Secara umum tingkat pemanfaatan lahan untuk kegiatan perikanan budidaya masih rendah yaitu baru mencapai 957 ribu hektar atau 5,35%, sehingga potensi pengembangan lahan masih sangat besar. Tingkat pemanfaatan lahan dari yang terendah secara berturut-turut adalah budidaya laut 276 ribu hektar (2,28%); budidaya air tawar 148 ribu hektar (5,26%); dan budidaya air payau 532 ribu hektar (17,96%) (KKP 2019). Dilihat dari wilayahnya, Jawa dan Sulawesi adalah wilayah yang tertinggi tingkat pemanfaatannya masing-masing 14,27% dan 13,48%, sedangkan Papua adalah wilayah yang terendah tingkat pemanfaatannya yaitu hanya 0,13%.
Ketiga, Beberapa komoditas unggulan memiliki daya saing yang tinggi di pasar ekspor dan mampu berperan sebagai penopang ketahanan pangan. Komoditas ekspor antara lain udang, rumput laut, kerapu, nila, dan lobster. Sementara, komoditas untuk memenuhi ketahanan pangan meliputi lele, patin, mas, gurame, bandeng, kakap, bawal bintang, dan ikan lokal.
Keempat, Indonesia memiliki potensi tenaga kerja yang besar, karena sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan yang memiliki potensi usaha perikanan budidaya, terlebih lagi penduduk yang tinggal di daerah pesisir. Apabila jumlah penduduk yang besar dapat ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya mengenai perikanan budidaya, maka ini dapat secara langsung menunjang peningkatan produksi perikanan budidaya.
Kelima, Teknologi pembudidayaan ikan telah dikuasai, baik oleh lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ditjen Perikanan Budidaya telah menguasai dan menerapkan teknologi terbaru perikanan budidaya, untuk selanjutnya didiseminasikan kepada pembudidaya ikan.
Keenam, Tersedianya sistem jaminan mutu produk perikanan budidaya yang telah konsisten diterapkan mulai dari tahapan pembenihan hingga tahapan pembesaran melalui penerapan sistem sertifikasi CPIB, sertifikasi CBIB, registrasi pakan, registrasi obat ikan, pengendalian residu dan surveilan dan monitoring penyakit. Sistem jaminan mutu akan meningkatkan keamanan pangan dan daya saing produk perikanan budidaya di pasar dunia.
Pengelolaan Belum Maksimal
Bahwa pada prinsipnya sumberdaya alam (natural resources) mempunyai pengertian segala sesuatu yang berada dibawah atau diatas bumi, termasuk tanah itu sendiri. Sumberdaya alam mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu Negara (khususnya Negara sedang berkembang), dimana semakin tinggi pertumbuhan ekonominya, akan mengakibatkan persediaan sumberdaya alam yang tersedia akan semakin berkurang. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan selalu menuntut adanya barang sumberdaya dalam jumlah yang tinggi pula, dan barang sumberdaya ini diambil dari persediaan sumberdaya alam yang ada. Dengan demikian, terdapat hubungan yang “positif” antara jumlah barang sumberdaya dengan pertumbuhan ekonomi, disamping juga hubungan yang “negative” antara persediaan sumberdaya alam dengan pertumbuhan ekonomi.
Kenyataan di atas memberikan peringatan kepada kita bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, apabila dilakukan tidak secara berhati-hati akan dapat mengguras persediaan sumberdaya alam yang ada. Kondisi ini pada gilirannya nanti akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya alam dalam rangka pembangunan harus dilakukan secara bijaksana, dengan senantiasa mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya.
Ikan adalah salah satu bentuk sumberdaya alam yang bersifat renewable atau mempunyai sifat dapat pulih/dapat memperbaharui diri. Disamping sifat renewable, menurut Widodo dan Nurhakim (2002), sumberdaya ikan pada umumnya mempunyai sifat “open access” dan “common property” yang artinya pemanfaatan bersifat terbuka oleh siapa saja dan kepemilikannya bersifat umum. Sifat sumberdaya seperti ini menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain tanpa adanya pengelolaan akan menimbulkan gejala eksploitasi berlebihan (over exploitation), investasi berlebihan (over investment) dan tenaga kerja berlebihan (over employment).
Demikian pula, untuk itu perlu adanya hak kepemilikan (property rights), misalnya oleh Negara (state property rights), oleh masyarakat (community property rights) atau oleh swasta/perorangan (private property rights). Dengan sifat-sifat sumberdaya seperti diatas, menjadikan sumberdaya ikan bersifat unik, dan setiap orang mempunyai hak untuk memanfaatkan sumberdaya tersebut dalam batas-batas kewenangan hukum suatu Negara.
Kondisi diatas mengakibatkan sumberdaya milik bersama seperti halnya sumberdaya ikan adalah memungkinkan bagi setiap orang atau perusahaan dapat dengan bebas masuk untuk mengambil manfaat. Selanjutnya, dengan adanya orang atau perusahaan yang berdesakan karena mereka bebas masuk, maka akan terjadi interaksi yang tidak menguntungkan dan secara kuantitatif berupa biaya tambahan yang harus diderita oleh masing-masing orang atau perusahaan, sebagai akibat keadaan yang berdesakan tersebut. Dengan demikian, secara prinsip sumberdaya milik bersama yang dicirikan dengan pengambilan secara bebas maupun akibat-akibat lain yang ditimbulkan seperti biaya eksternalitas (disekonomis) dan lain sebagainya, akan menimbulkan kecendrungan pengelolaan secara alamiah, dalam arti tidak ada kreativitas dan inovasi.*** (BERSAMBUNG).
*** Notaris, Doktor Kehutanan Unmul Samarinda, Pengurus Pusat INI (Ikatan Notaris Indonesia) Universitas Diponegoro, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit Kalimantan Tengah.