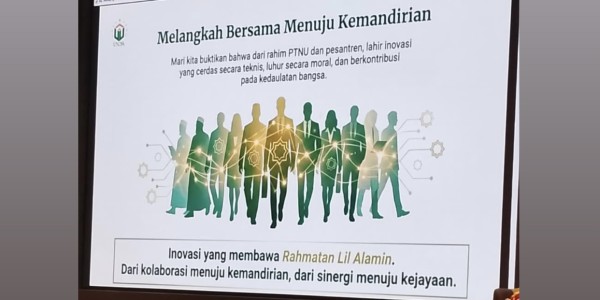telusur.co.id - Oleh : Denny JA
Sebuah Puisi Esai tentang Bencana Sumatra dan Luka Ekologis (12)
(Dalam bencana Sumatra yang menelan lebih dari seribu nyawa, seorang psikolog di pengungsian menyimpulkan: luka batin para korban lebih berat dibanding korban Tsunami Aceh dua puluh satu tahun sebelumnya.)
Dewi menangis,
air matanya deras sekali,
seperti tanah yang lama kering,
lupa bagaimana caranya bersuara;
ketika hujan pertama datang,
ia menyerah
tanpa perlawanan.
Tangis itu tidak meledak.
Ia tinggal
sebagai garis tipis
di wajah seorang psikolog
yang terlalu lama
mendengar cerita orang lain
tanpa bisa mengubah naskah.
“Aku pernah ke sini,” katanya pelan, seperti orang
yang menyadari kesalahan lama tak pernah benar-benar pergi.
“Aku menangani tsunami Aceh.”
Ia menyeka matanya.
Namun air mata tetap turun
seolah tubuhnya
lebih jujur
daripada laporan-laporan resmi.
“Yang ini,” katanya lagi,
suara itu hampir pecah
di antara hujan dan kain tenda,
“lebih berat.”
Bukan karena airnya lebih tinggi,
melainkan karena
ia datang
lagi dan lagi,
menjadi sesuatu
yang lama-lama dianggap biasa.
Hujan kini
tak lagi terasa datang dari langit.
Ia seperti muncul
dari bawah kaki.
Dari peta-peta
yang berubah pelan-pelan,
dari warna hijau hutan,
yang menghilang
tanpa upacara perpisahan.
Setiap tetes membawa cerita kecil:
nama anak yang tak sempat diselamatkan,
buku sekolah yang mengembang basah,
rumah yang hanyut
tanpa tahu
siapa yang lebih dulu
menggunduli hulunya.
Di tenda pengungsian
yang berbau lumpur, plastik,
dan janji yang tak kunjung datang,
Dewi duduk.
Diam.
Ia menjadi lemari tua
penuh berkas,
rapi, berat,
namun jarang dibuka
saat paling dibutuhkan.
Dua puluh satu tahun lalu,
2004,
air tsunami datang
seperti singa.
Ia menyerang sekali,
lalu pergi.
Luka besar,
namun jelas asalnya:
datang dari laut,
kembali ke laut.
Dunia tahu
apa yang harus dilakukan.
Sekarang berbeda.
Sekarang air datang
seperti tikus kecil:
tak menakutkan,
tak masuk berita besar,
namun tak pernah berhenti
menggerogoti hidup.
Ia datang dari bukit
yang dipotong pelan-pelan,
dari hutan
yang dirayakan saat tumbang,
dari sungai
yang dipersempit
agar kota tampak rapi
di brosur pembangunan.
Setiap hujan
menjadi pertanyaan.
Setiap awan
menjadi peringatan.
“Bu,”
kata seorang gadis kepada Dewi,
“airnya tidak besar.
Tapi kenapa
aku selalu merasa
hidup kami
sebentar lagi
jatuh?”
Dewi tahu jawabannya.
Namun jawaban itu
terlalu besar
untuk ruang terapi.
Ini bukan trauma
yang jatuh dari langit.
Ini trauma
yang disiapkan pelan-pelan
di ruang rapat berpendingin udara.
Trauma yang tidak berteriak,
hanya duduk di dada,
menunggu hujan berikutnya
untuk bangun kembali.
Di tenda sebelah,
seorang ayah membentak anaknya karena sendok plastik jatuh.
Bukan sendok yang membuatnya marah,
melainkan hidup
yang tak pernah bertanya
apakah ia masih sanggup.
Air bersih datang
tak menentu.
Toilet hanya ada
setengah jadi,
seperti janji
yang takut diwujudkan.
Bahkan
untuk menyendiri pun,
mereka
tak diberi ruang.
Trauma, pikir Dewi,
bukan hanya luka di kepala.
Trauma adalah
dipaksa tinggal
di tempat
yang kita tahu
akan rusak lagi.
Di sela konseling,
Dewi menatap sungai
yang meluap perlahan,
seperti orang tua
yang terlalu sering
dikhianati.
Ia teringat peta-peta
di meja kebijakan:
hutan dipotong
bagai kalimat yang dianggap tak penting.
Bukit dikupas
menjadi kulit mati,
padahal di situlah
air dulu bisa ditahan.
Air, kini ia mengerti,
tak pernah berniat jahat.
Ia hanya berjalan
mengikuti ruang
yang kita rusak sendiri.
Bencana ini
bukan amarah alam.
Ia hasil dari
keserakahan
yang lupa belajar
berhenti.
Malam itu,
di buku catatan
yang lembap oleh hujan,
Dewi menulis:
“Ini mungkin tugasku yang terakhir.”
Bukan karena ia tak peduli,
melainkan karena ia lelah
menjahit luka
sementara
luka baru
terus disiapkan.
Ia ingin pulang.
Menjadi manusia biasa,
yang boleh gemetar
tanpa perlu
dihitung
dan diukur.
Saat Dewi pergi,
hujan turun lagi.
Tidak deras,
hanya cukup
untuk membuat rindu.
Namun hujan kecil
adalah yang paling lama tinggal.
Ia datang berkali-kali,
hingga manusia
belajar hidup
dalam cemas
sebagai kebiasaan.
Dan bumi,
tanpa marah,
tanpa ancaman,
berkata pelan:
Aku tidak sedang menghukummu.
Aku hanya mengikuti
pilihanmu.
Itulah sebabnya,
bagi Dewi,
bagi para pengungsi,
bagi anak-anak
yang tidur dengan sepatu di kaki,
bencana ini
lebih berat
dibanding tsunami.
Karena tsunami
datang sebagai tamu
dan pergi.
Yang ini
adalah rumah
yang runtuh
karena kita menyebut
perusakan
sebagai pembangunan,
dan tak pernah tuntas menyebut
siapa yang harus
bertanggung jawab.
*Penulis adalah Konsultan Politik, Founder LSI-Denny JA, Penggagas Puisi Esai, Sastrawan, Ketua Umum Satupena, Penulis Buku, dan Komisaris Utama PT. Pertamina Hulu Energi (PHE).