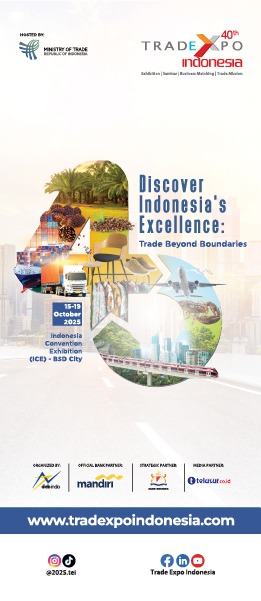Telusur.co.id - Oleh: Dr. Margarito Kamis, SH. M.Hum
Fox populi vox dey (suara rakyat, suara tuhan), membahana di Eropa pada abad pertengahan. Dimengerti dan disambut sebagai sebuah temuan paling mengagumkan, karena konsep itu menandai dan menempatkan setiap orang sebagai manusia mulia, karena dilengkapi dengan serangkaian hak. Hak yang dilengkapi itu, dalam temuan ini, diterima sebagai sesuatu yang ada dan melekat pada setiap orang.
Kualitas dan sifat hak itu, dalam konsep ini, alamiah. Alamiah, karena hak itu ada dan melekat pada setiap orang bukan karena kreasi atau diciptakan oleh hukum positif. Sama sekali tidak. Hak itu ada dan melekat pada setiap orang, karena hak itulah yang menandai eksistensi setiap orang sebagai manusia.
Tanpa hak itu, manusia diterima, tidak lebih, kecuali hanya itu, sebagai property. Diantara sejumlah hak yang disematkan Tuhan kepada setiap orang, yang ditandai oleh berbagai ilmuan sebagai akar dari sifat alamiahnya, adalah hak menyatakan kehendak. Tanpa hak menyatakan kehendak, termasuk memilih sesuatu yang sesuai kodratnya, tidak seorangpun dapat eksis sebagai manusia mulia.
Itu sebabnya para ilmuan mensifatkan kehendak sebagai cermin eksistensi merdeka dan mulianya setiap orang sebagai manusia. Tetapi semegah dan seindah itu sekalipun konsep pengagungan manusia, yang dalam sentuhan menakjubkan John Bodin, ilmuan politik kawakan abad ke-16 ini sebagai sovereign atau “superanus” dalam bahasa latin. Tetapi tetap saja tak dapat dipakai untuk menyangkal kenyataan lain, yang dalam semua aspeknya menggelitik.
Kenyataan itu adalah orang-orang tertentu dari kelas atas, entah itu para aristokrat atau satria dan orang-orang berduit dalam kasus Inggris abad ke-14 dan abad ke-17, berada di front utama usaha mengubah status orang dari semula tidak merdeka menjadi merdeka. Mengubah status orang dari tak merdeka menjadi merdeka, bernilai fundamental menghadirkan tatanan baru.
Tatanan yang dihasilkannya itu disebut civilization. Dalam revolusi Perancis, tatanan baru tersebut disebut atlantic civilization. Suka atau tidak, mereka, orang-orang berduit inilah, yang menemukan dan mendesakan daulat rakyat. Eksis sebagai ciptaan cerdas kalangan atas, tentu dengan berbagai alasan, suka atau tidak, selalu menyediakan cacat esensial.
Dalam kasus Prancis, sejauh terekam dalam sejarah, daulat rakyat datang lebih belakangan dari Inggris. Prancis yang rajanya dibakar ambisi untuk menyeragamkan Eropa kedalam satu keyakinan agama, (catatan level sensifitasnya mengisolasi saya untuk tidak menuangkannya kedalam artikel ini), berhasil membawa raja Inggris sebarisan dengannya. Sikap raja Inggris itu menjadi salah satu sebab terbesar terjadinya Glorius Revolution, yang menggulung raja.
Kombinasi cerdas antara sikap raja Inggris yang mau sebarisan dengan raja Prancis di satu sisi, dan kaum Whig yang berisi para pedagang kaya cerdik terorganisir, menghasilkan kebutuhan untuk membuat revolusi. Tak berhenti disitu, kaum Whig, segera bekerjasama dengan politisi parlemen. Hasilnya segera terlihat, terjadi revolusi Inggris 1688.
Revolusi ini menggulung apa yang disebut Francis Bacon “King as nation, and King as State” menurut konsep konstitusi Inggris kala itu. Praktis revolusi itu menggulung serangkaian hak prerogatif raja. Cerdiknya, parlemen yang bersama-sama kalangan Whig menentang kerajaan, mengambil langkah struktural hebat.
Gagasan civilian, khas republik segera dirumuskan “positum” kedalam Bill of Rights. ”Positum” atas ragam hak individu dalam Bill of Rights, di antaranya pembatasan hak raja membebani pajak kepada setiap individu. Kerajaan, dalam bill right itu dapat memungut pajak sejauh telah diatur dalam UU. Privilege individu tertentu, misalnya diberi hak memiliki pasukan regular, dihilangkan. Tidak seorangpun dapat dituntut tanpa berdasarkan undang-undang.
Bill of Rights 1689, andai hendak diperiksa deteilnya, akan ditemukan kesamaan substansialnya dengan serangkaian hal yang telah “dipositumkan” dalam Petition of Right 1628. Petition of Rights ini terbentuk atas gagasan original Sir Edward Coke, hakim pada pengadilan Kerajaan, yang sejak 1626 beralih menjadi anggota parlemen.
Capaian mengagumkan revolusi gemilang itu, sayangnya tereksklusivisasi. Nadanya tak harmonis. Menariknya capaian itu selalu dan hanya itu ditandai sebagai terkonsolidasinya gagasan rule of law. Tidak salah. Demokrasi juga begitu, menyajikan revolusi itu dalam irama dan nuansa yang mirip dengan rule of law.
Konsekuensinya, tatanan baru menandai naiknya gagasan “daulat rakyat.” Tetapi pembicaraan mengendai daulat rakyat, sejauh ini, terlalu sering dilepaskan dari kenyataan sepak terjang oligarki. Itu pembicaraan-pembicaraan, etrasa sulit untuk tak mengatakanm tak memiliki nada dan nuansa revisionis. Suka atau tidak, dalam kenyataannya semua aspek penyelenggaraan negara tidak simetris dengan kemauan rakyat.
Hebat, itulah kecerdikan kaum kaya mengagungkan orang kebanyakan dan menyebutnya sebagai people. Tak berhenti disitu, people juga dijadikan sumber kekuasan. Mereka supreme. “Daulat rakyat dan suara rakyat, suara Tuhan” sejatinya merupakan kreado kaum oligarkis. Kredo itu hanya indah dan mengagumkan secara simbolik. Tak lebih.
Suara rakyat yang di-maksimkan- sebagai suara tuhan itu, karena komplikasi teknisnya, diwakilkan kepada anggota parlemen. John Locke, ilmuan politik hebat ini menyifatkan parlemen sebagai poros kekuasaan, dan berstatus supreme. Negara, begitu asumsi Locke, diselenggarakan atas dasar people will and expectation, bukan kemauan King, noble man, aristokrat dan lainnya yang sejenis.
Dalam konteks itu ditampilkan, sesuai asumsi Locke, yang diterima oleh sejumlah ilmuan sebagai cerminan kehendak rakyat. Mungkin ini disebabkan Locke juga Edward Cooke, konstitusionalis paling termashur pada masanya, tidak menyaksikan hasil kerja kaum oligarki sesudah Glorius Revolution.
Semua hasil cepat revolusi itu, untuk alasan apapun merupakan capaian terbesar kaum oligarki, bukan rakyat kebyakan. Sebabnya adalah sejak tahun 1670 atau 18 (delapan belas tahun) sebelum revolusi hebat itu, kalangan oligarki, ambil misalnya John Houblan, dan Michael Goldfrey, yang Plamen Ivanov, dalam disertasinya “The Bank of England….., pada University of Southampton, sebut “prominent Whig merchants” telah berusaha dan mempromosi pembentukan bank umum.
Usaha Houblon diwujudkan dengan cara, pertama bersama dengan Michael Goldfrey, prominent leader lain dalam London Merchants Community, segera membuat petisi kepada kerajaan. Isi petisinya, kerajaan harus memilik satu bank umum. Tak lama setelah petisi heboh itu diajukan, kedua, Houblon dan Goldfrey segera mengadakan kunjungan dangang ke Amsterdam. Di Amsterdam, Houblon dan Goldfrey mengadakan serangkaian loby dengan kalangan pedagang Belanda.
Lobi mereka memberi hasil. Terjalinlah kerjasama antara mereka dengan kalangan pedagang Amsterdam. Menarik, keduanya juga mempelajari cara kerja Amsterdamche Wisselbank, bank yang telah sukses sejak 1609. Tetapi yang jauh lebih menarik adalah sikap Wiliiam of Orange, dikenal dengan William III, orang Belanda ini menjadi Raja Inggris setelah Glorius Revolution. Status itu disandang bersama Mary, istrinya, sebagai Ratu. Praktis Inggris memiliki Ratu dan Raja pada waktu bersamaan, sesuatu yang belum ada presedennya.
William, si orang Belanda, yang telah dijadikan Raja Inggris ini, dalam kenyataannya, memberi dukungan penuh terhadap pembentukan Bank of England. Setelah meneria proposal pembentukan bank dari sebagian anggota Parlemen, William memerintahkan Privy Councel mempelajari proposal tersebut.
Dimana rakyat, people, dalam hiruk-pikuk pembentukan Bank of England? Tak terlihat sama sekali. Panggung tatanan baru, new order, yang telah tercivilisasi dikuasai penuh kalangan oligarki. Dipanggung utama menjelang pembentukan Bank of England, muncul nama William Petterson, dan Charles Montagu, Chancellor of the Exchaquer sebagai dua pioneernya.
Keduanya memainkan peran satu dan lainnya berbeda, tetapi berakhir dengan hasil yang sama. Montagu tidak ke Amsterdam, sedangkan Petterson disisi lain justru ke Amsterdam pada tahun 1607, setahun sebelum Glorius Revolution. Montagu, sang komisioner keuangan itu, habis-hebis melobi parlemen untuk pendirian bank itu. Dukungan Montagu menjadi faktor kunci perubahan persepsi masyarakat atas Bank yang direncanakan itu.
Memang perjalanan Petterson ke Amsterdam dibimbing oleh amibisinya memperoleh dukungan kalangan padagang Amsterdam kepada dirinya memperoleh tambahan modal dari mereka untuk usahanya mendirikan bank yang sama di Panama. Menarik, niat mendirkan bank yang sama di Panama menghilang dari kepalanya seketika setelah ia menginjakan kakinya kembali di Inggris.
Haluan mimpinya berganti, dan kini tertuju pada percepatan pendirian Bank of England. Terbakar oleh mimpi itu, Petterson yang didukung oleh penuh kelompok business man dikota London, segera menjalin hubungan dengan anggota parlemen dari kalangan Wigh.
Petterson tahu, kalangan Tories berada diseberang, beroposisi terhadap gagasan pendirikan Bank, sehingga Petterson harus segera menemukan cara meredamnya. Menyesatkan masyarakat, itu yang melintasi dipikirannya, dan diwujudkan dengan menyebarkan pamphlet-pamflet tentang pentingnya Inggris memiliki satu bank umum.
Cara ini, terlihat nyata mengilhami kalangan oligarkis Amerika dalam usaha yang sama. Ketika sekelompok oligarki Wall Street, misalnya Jacob Schiff, J.P. Morgan, Rockeffeler, melintasi jalan politik menanjak mendirikan The Fed,s mereka juga menggunakan cara yang sama.
Kenyataannya kas negara sedang kosong, sementara kalangan tertentu sedang terbakar ketidaksukaan kepada Prancis, dan hendak memerangi Prancis, mungkin menjadi factor penentu suksesnya gagasan pendirian bank of England. Konsekuensi jelas. Kerajaan harus punya uang untuk membiayai perang. Uang itu hanya bisa didapat melalui para oligarkis, yang menghendaki pendirian bank ini.
Parlemen yang memang telah sehaluan dengan William, tak memiliki pilihan lain selain harus membentuk UU untuk tujuan itu. Menurut Petter Howells dari Departemen of Accounting, Economic and Finance University of West England, parlemen Inggris, hebatnya tidak membentuk UU yang diberi nama Bank Act. Nama yang digunakan adalah Ways and Meant Act, dibentuk pada bulan Juni 1694, yang sering disebut “Tonnage Act. UU berfungsi sebagai dasar Kerajaan menarik tax revenue setiap kapal dan penggunaan wine, yang ditampung di bank ini.
Tahu William telah memberi atensi dan sepenuhnya menghendaki pendirian bank, UU ini memberi otoritas kepada kerajaan mengeluarkan “Royal Charter” sebagai dasar pendirian bank. Masa operasi Bank dibatasi, dan perpanjangan operasinya juga dilakukan berdasarkan Royal Charter, recharter.
Setelah terbentuk, rakyat Inggris yang telah berdaulat menemukan kenyataan John Houblon, orang yang sejak tahun 1670 telah mengusahakan pendirian bank ini, menjadi Gubernurnya yang pertama. Houblon hebat, selain menjadi gubernur pertama bank ini, adik-adiknya (Abraham Houblon dan James Houblon) juga memasuki bank melalui sejumlah saham. Praktis keluarga ini mendominasi daftar pemegang saham bank ini.
John Houblon, dibantu oleh John Somers, sebagai Lord Keeper, dan Michael Goldfrey sebagai deputi gubernur. Oligarki-oligarki tentu riang, dengan semua yang dicapai ini. Bank kepunyaan sendiri, menampung uang-uang orang lain, lalu mengurus sendiri uang itu, meminjamkan kepada orang lain, menarik bunga, dan lainnya secara manduiri. Itulah oligarki.
Oligarkis selalu begitu, mengakali negara, menggunakan negara untuk kepentingan mereka. Oligarki merchant London, khususnya pedagang sutra, juga menggunakan UU memastikan kelangsungan dagang mereka disatu sisi, dan memukul pesaingnya disisi lain. Caranya sama, menggunakan UU. UU dimaksud adalah Sumptuary Act 1732, yang pembentukannya diprakarsai oleh oligarki sutra Persia.
Oligarki memang kelewat, entah pintar, cerdas, cerdik, licik, kreatif, inovatif atau lainnya, tetapi memang harus diakui kecepatan imajinasi mereka tak bakal terkejar oleh rakyat kebanyakan. Takdir republik bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, hanya asyik untuk imajinasi republik itu sendiri. Tak lebih.
Apakah wacana panas tentang penundaan pemilu saat ini, yang memiliki relasi kuat dengan kehendak para pengusaha, sesuai penuturan Bahlil, menandai nuansa oligarkis? Entahlah. Ini disebabkan Edwin Aksa, mantan Ketua HIPMI itu, menolak gagasan yang rakyat berdaulat melebelnya sebagai konyol, ngawur dan sejenisnya itu.
Konyol, ngawur dan sejenisnya terlihat mewarnai gasan itu, dihadapkan pada pertanyaan siapa yang memiliki wewenang menunda pemilu? Siapa atau lembaga apa yang berwenang memperpanjang masa jabatan Presiden, anggota DPR dan anggota DPD? Presiden, DPR, DPD, MPR termasuk KPU, semuanya, tidak memiliki wewenang itu. Tidak, apapun alasannya.
Banyak memang duri-duri konstitusional yang menantang gagasan itu, tetapi andaikan pengusaha-pengusaha yang disebut Bahlil telah memiliki tabiat oligarki, pasti mereka memiliki keyakinan dan cara meraih suksesnya gagasan itu. Semakin mudah mencapainya bila mereka telah mengetahui Enabling Act 1932. UU inilah yang dipakai Adolf Hitler, yang totaliter itu merajut kekuasaannya.
Adolf Hitler memasuki kekuasaan secara demokratis. Partai Nazi, yang diketuainya mengikuti pemilu dengan donasi dari sejumlah oligarki Amerika dan Jerman. Hitler memperoleh suara terbesar, membawanya memasuki kekuasaan dengan membentuik kabinet. Setelah berkuasa, Hitler membuat Anabling Act 1932, menggunakan UU itu menangguhkan konstitusi Weimar 1919, yang sangat demokratis itu.
Hitler mengarungi kekuasaannya dengan semua cara, yang hingga saat ini dinilai menjijikan. Tangan besi Hitler mengandalkan polisi rahasia, yang pembentukannya digagas oleh Herman Goring. Manusia ini juga yang dipercayai Hitler menjadi Kepala Polisi rahasia pertamanya. Siapa saja yang bicara sosialisme tulen, apalagi liberalisme, ditangkap. Siapa saja yang berseberangannya, ditangkap.
Kenyataan sejarah itu harus menggoda rakyat, yang katanya berdaulat, untuk menimbang secara jernih gagasan penundaan pemilu. Pemilu memang bisa ditunda, tetapi hanya melalui UU, termasuk pakai Perpu. Hanya Presiden, menurut UUD 1945, yang memiliki wewenang buat Perpu, dan meminta persetujuan DPR.
Bila Presiden Jokowi memiliki keberanian membuat Perpu penundaan pemilu, itu baru satu langkah. Langkah lain yang harus dilakukan adalah ubah konstitusi. Sebab, masa pemilu jelas, 5 (lima tahun) sekali. Masa jabatan presiden juga sama, 5 (lima tahun). Konsekuensinya, setelah terbit Perpu, Presiden harus segera berusaha mengubah pasal-pasal masa pelaksanaan pemilu dan masa jabatan Presiden dalam UUD 1945.
Kecuali dalam alam totaliter, tidak tersedia alasan lain dalam alam demokrasi untuk mengabaikan prosedur diatas. Tetapi apakah kalangan pengusaha yang disebut Bahlil akan habis-habisan tetap kukuh menghendaki perpanjangan masa jabatan presiden, dengan risiko-risiko di atas? Pengusaha-pengusaha yang memiliki mimpi perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, sebaiknya belajar cara oligarki Amerika bekerja mengendalikan pemerintah.
Apapun itu, agar tak terkangkangi, rakyat berdaulat pantas meletakan kasus Bank of England dan sepak terjang totaliter Hitler, dalam menimbang semua detail yang terlihat maupun tak terlihat pada gagasan penundaan pemilu itu. Apakah pengusaha-pengusah itu telah memiliki kapasitas oligarki? Entahlah. Sejarah jelas dalam soal ini, oligarki selalu cerdas menemukan cara memastikan kemenangan mereka.