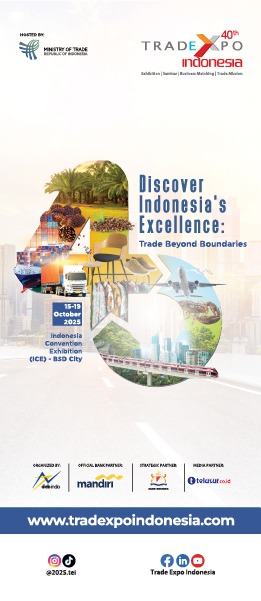telusur.co.id – Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), semestinya tidak melulu dimaknai sebagai upaya dekolonisasi hukum pidana Indonesia. Tetapi, juga sebagai bagian dari demokratisasi hukum pidana.
Demikian disampaikan oleh Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada telusur.co.id, Jumat (20/9/19).
“Karena itu RKUHP juga tidak boleh mendegradasi tindak pidana yang bersifat khusus dan extra ordinary crimes menjadi tindak pidana umum, sehingga tidak memerlukan lagi cara penanganan yang luar biasa, pada gilirannya menghapuskan peran lembaga yang menanganinya seperti KPK,” kata Fickar.
Menurut Fickar, dibutuhkan pasal yang menyatakan ketentuan undang-undang khusus pidana tetap berlaku.
Ia juga menguraikan beberapa tindak pidana yang dianggap masih bermasalah, antara lain: Pasal 2 ayat (1), Pasal 598 RKUHP, soal hukum yang hidup di masyarakat.
Bagi dia, ketentuan ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam UU ini.
“Pasal yang mengatur hukum yang hidup dalam masyarakat ini mengandung penyimpangan asas legalitas dan kriminalisasi yang tidak jelas,” tegasnya.
Bahkan, lanjut dia, pasal ini dapat menimbulkan kesewenangan aparat karena frasa hukum yang hidup di masyarakat multitafsir, dan tafsir hilangnya sifat melawan hukum delik materil, bisa menjadi ketentuan karet.
Kemudian, Pasal 67, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101 dalam RKUHP, soal hukuman mati. Hukuman mati, tutur Fickar, seharusnya dihapuskan saja. Karena bertentangan dengan Pasal 28i Undang-Undang Dasr 1945.
“Demikian juga sesuai dengan perkembangan bahwa 2/3 negara di dunia sudah mengahapuskan hukuman mati,” imbuhnya.
Selain itu, pemberian masa percobaan untuk menunda eksekusi pidana mati semestinya menjdi hak setiap orang yang diputus dengan pidana mati. “Tidak boleh bergantung pada putusan hakim,” tukasnya.[Ham]