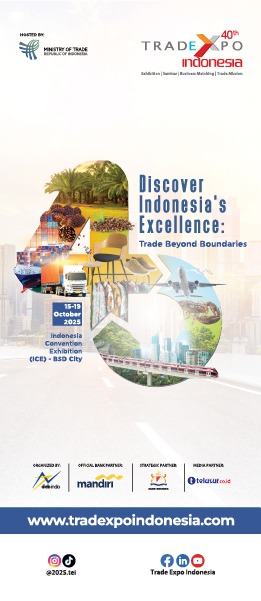Oleh: SUROTO*
Agar kekuasaan tak absolut ada di tangan seorang raja, maka Montesquieu mengusulkan perlunya pembagian kekuasaan menjadi tiga yang terkenal dengan istilah Trias Politica. Kuasa pembuat aturan (legislatif), pelaksana (eksekutif) dan kuasa pengadilan (yudikatif).
Tapi, benarkah kekuasaan itu terbagi sedemikian rupa? Ataukah hanya bersifat administrasi semata?
Trias politica seakan telah memberikan makna bahwa kekuasaan raja itu tidak mutlak lagi. Sistem autokrasi juga seakan telah punah ketika sistem demokrasi atau suara rakyat itu diterapkan.
Padahal, faktanya dalam praktek kekuasaan itu ternyata tetap absolut. Suara parlemen adalah lagu koor nyanyian setuju. Pengadilan ternyata hanya untungkan mereka yang dekat dengan kekuasaan, tajam ke bawah tumpul ke atas.
Contoh paling gamblang bagaimana mesin politik autokratif itu bekerja adalah lolosnya UU Omnibus Ciptakerja yang dipaksakan hanya demi melindungi segelintir kepentingan elit kaya.
Contoh lain dari perspektif hukum adalah tumpulnya putusan pengadilan atas kasus Kendeng yang jelas putusan Pengadilan sudah menyatakan inkracht dimenangkan Sedulur Sikep namun hanya dianggap angin lalu.
Pabrik Semen itu tetap menggencet anak turun Samin yang juga berarti menggencet seluruh rakyat Indonesia.
Peraturan disusun bukan untuk melindungi yang lemah namun dijadikan rompi pengaman bagi kepentingan kekuasaan. Pengadilan tidak lagi dihargai kehormatanya.
Suara rakyat ternyata hanya semacam seonggok kartu suara di kala musim pemilu tiba. Semua tak berguna. Para politisi itu hanya sibuk bekerja demi pencitraan melalui jualan gimmick dan iklan. Mereka hanya pandai buat jargon dan slogan jualan harapan, tidak dalam tindakan.
Begitu pesta pora pemilu usai, apa yang mereka kampanyekan itu tak ada yang dilakukan, dan apa yang tak dikatakan justru mereka kerjakan. Ini seperti terus berjalan sebagai hukum besi kekuasaan.
Sebut misalnya, untuk merebut hati rakyat banyak, politisi itu katakan akan bela habis habisan ekonomi rakyat. Tapi begitu berkuasa mereka kempongi usaha rakyat dengan fokus berikan seluruh fasilitas bagi kepentingan bisnis swasta konglomerat.
Parahnya lagi, saat ini para konglomerat republik ini tak hanya telah berhasil kangkangi sumberdaya ekonomi kita, tapi mereka telah rebut seluruh aspirasi politik rakyat karena kursi legislatif dan eksekutif di seluruh tingkatkan diborong semua oleh mereka. Mereka merajalela dalam sistem kuasa Plutogakhi, kuasa sublim hasil kawin silang elit kaya dan elit politik.
Kalaupun ada aspiran dari kelompok termarjinalkan, mereka ditempatkan hanya sebagai anak bawang, terlibat tapi tak mempengaruhi apapun. Mereka itu adalah politisi dormant, hanya semata berkepentingan atas kebutuhan imannen sehari hari, poliisi kelas isi perut mereka sendiri.
Memang, sesunguhnya sifat kekuasaan itu sendiri sebetulnya tak ada yang tunggal, singular. Sekalipun sistem monarkhi ditegakkan selurus lurusnya. Raja tetap tak dapat lepas dari kepentingan tekanan politik dari berbagai pihak. Kekuasaan itu bersifat majemuk, dan ini menurut hemat penulis begitu adanya sejak istilah kekuasaan itu pertama disebut.
Seorang Jokowi tentu terlihat lebih berkuasa ketimbang Suroto peternak kecil ayam petelur dari Blitar yang sempat diinterograsi Polsek setempat karena bentangkan protes soal harga jagung yang membumbung. Tapi apakah seorang Jokowi lalu bisa dikatakan lebih berkuasa dari seorang Putera Sampoerna, konglomerat Indonesia ?
Lalu apakah sebetulnya yang berlaku dari hukum politik kita saat ini ? Trias politica atau Mono Politica? Lalu dimana kedaulatan rakyat itu sejatinya?[***]
*) Ketua AKSES - INDONESIA (Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis) dan CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR Federation)